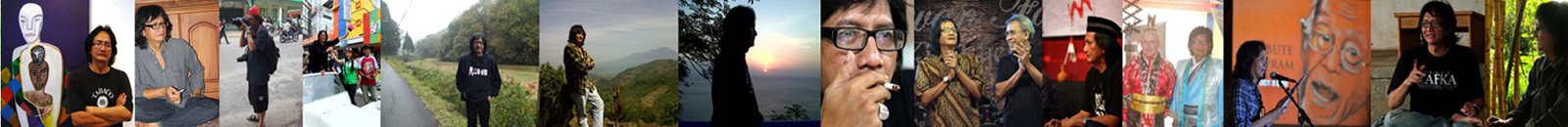LANJONG MELANCONG
Acep Zamzam Noor
Acep Zamzam Noor
SEKITAR April 2009 seorang teman mengundang saya untuk mengisi salah satu acara pada Lanjong Art Festival, sebuah festival dua tahunan yang sudah beberapa kali digelar di Tenggarong, Kalimantan Timur. Tentu saja saya merasa senang sambil diam-diam membayangkan bagaimana sebuah festival kesenian digelar di daerah yang infrastrukturnya mungkin belum memadai, yang jarak antara satu kota ke kota lainnya berjauhan serta harus ditempuh dengan melewati hutan. Saya juga membayangkan kesenian macam apa saja yang akan ditampilkan pada festival tersebut, apakah tradisional, modern atau kontemporer. Bukankah kesenian kontemporer kini sudah merambah ke mana-mana, termasuk ke pelosok Kalimantan?
Beberapa tahun sebelumnya saya sempat melawat ke kota kecil yang pusat keramaiannya berada di sekitar sungai Mahakam itu. Sebuah kota yang indah, begitulah kesan saya, apalagi jika mengunjungi kota tersebut pada saat menjelang senja. Ada jembatan yang melengkung, ada patung lembu yang monumental, ada pulau di tengah-tengah sungai yang lebar. Perahu-perahu nelayan hilir mudik, begitu juga kapal yang mengangkut batu bara, dan di sepanjang tepian sungai yang pelatarannya sudah dibeton banyak anak-anak muda main sepatu roda. Jembatan yang melengkung itu konon meniru jembatan yang ada di San Francisco, dengan lampu-lampu kecilnya yang berkedip-kedip ketika senja dan malam tiba.
Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai Kertanegara, memang termasuk daerah yang pembangunannya pesat. Kantor bupatinya megah, begitu juga kantor DPRD yang hampir seluruh bagian mukanya dipenuhi dengan berbagai ragam hias. Sementara kantor-kantor dinas yang gedungnya kelihatan masih baru juga berkumpul di sekitar itu. Tak jauh dari jembatan nampak sebuah bukit yang dipenuhi bangunan-bangunan yang belum selesai, yang di antaranya hotel berbintang. Dan jika menyusuri ruas jalan ke arah utara kita akan bertemu dengan museum yang menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan lama. Reflika istana kerajaannya sendiri belum lama selesai direkonstruksi, letaknya tak jauh dari rumah dinas bupati. Meski semakin sayup suasana kota masih tersambung dengan rumah-rumah makan serta kios-kios souvenir sepanjang pinggir sungai.
Di tengah berbagai fasilitas pemerintah yang megah, saya membayangkan pasti terdapat juga gedung kesenian yang representatif, gelanggang olahraga yang lengkap atau sarana-sarana lain untuk aktivitas masyarakat. “Stadion sepakbola sudah lama dibangun, namun gedung kesenian belum ada,” ujar teman saya. Lalu teman saya tersebut menjelaskan bahwa hanya dalam radius sekitar dua kilo meter dari jembatan sudah bukan termasuk kota lagi, melainkan perkampungan biasa. Perkampungan dengan bentuk-bentuk rumah sederhana yang khas, rumah-rumah dengan atap seng. Tenggarong memang identik dengan jembatannya yang melengkung itu, di mana kantor bupati dan kantor DPRD sebagai pusat kekuasaan berada di hadapannya. Tiba-tiba saya merasakan sebuah ironi dari tata ruang kota ini, sebuah kontras yang tegas.
Dengan diantar teman saya memasuki perkampungan lebih dalam lagi. Di tengah-tengah perkampungan saya hampir tak menjumpai satu pun toko apalagi super market, yang ada hanya warung-warung kecil. Tapi yang kemudian membuat saya tertegun, saya menemukan banyak sekali papan nama dari berbagai komunitas kesenian. Ada yang menamakan komunitas tari, teater, musik, seni rupa dan semacamnya. Papan-papan nama yang dilengkapi logo serta nomer izin resmi tersebut terpasang di depan rumah, seperti halnya papan nama dokter atau pengacara yang membuka praktek.
“Di sini kesenian hidup di tengah masyarakat, banyak komunitas yang menghimpun anggota yang umumnya anak-anak dan remaja. Mereka secara rutin berlatih tari, teater, musik, senirupa dan sebagainya. Untuk teater atau senirupa biasanya dibimbing guru-guru SMK yang kebanyakan berasal dari Jawa, tapi kesenian yang ada kaitannya dengan tradisi dilatih seniman dari sini,” ujar teman saya yang berasal dari Yogyakarta. Kesenian-kesenian tradisional seperti tari dan musik, baik yang berbasis Melayu maupun Dayak sampai sekarang masih hidup.
Demikianlah, dalam atmosfirnya yang khas kegiatan kesenian terus berdenyut di Tenggarong. Setiap sore anak-anak dan remaja menari di halaman, di tempat lain sejumlah pemuda berlatih teater dan main musik. Ada juga yang teriak-teriak membaca puisi. Sementara ibu-ibu mudanya mengikuti senam aerobik dengan penuh semangat. Setiap komunitas mempunyai benderanya masing-masing, juga agendanya sendiri-sendiri. “Tapi kadang kita juga tampil bersama-sama. Tampilnya bisa di mana saja, bisa di lapangan, di gedung olahraga atau di kantor pemda. Untuk even tertentu malah sering diundang ke Taman Budaya Kaltim di Samarinda,” teman saya, yang juga melatih teater di salah satu komunitas, menjelaskan lebih jauh.
Kenapa komunitas-komunitas kesenian bisa terus hidup di Tenggarong? Di kota kecil yang minim sarana hiburan dan rekreasi ini, kesenian nampaknya mempunyai fungsi yang jelas. Bagi mereka yang menjadi anggota komunitas, kesenian merupakan media ekspresi serta sarana aktualisasi diri. Sementara bagi yang tidak terlibat secara langsung kesenian berfungsi sebagai pencerahan, paling tidak sebagai hiburan dan rekreasi. Dengan demikian, selain masyarakatnya yang memang membutuhkan, sedikit banyak pemerintah juga menyokong. Dalam hubungan timbal balik seperti inilah sebuah tradisi tercipta, yakni tradisi berkesenian. Dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri.
“Kesenian apapun yang digelar selalu banyak penontonnya,” lanjut teman saya yang mulai memperkenalkan latihan-latihan dasar teater mini kata kepada anak-anak didiknya yang masih remaja.
Beberapa tahun sebelumnya saya sempat melawat ke kota kecil yang pusat keramaiannya berada di sekitar sungai Mahakam itu. Sebuah kota yang indah, begitulah kesan saya, apalagi jika mengunjungi kota tersebut pada saat menjelang senja. Ada jembatan yang melengkung, ada patung lembu yang monumental, ada pulau di tengah-tengah sungai yang lebar. Perahu-perahu nelayan hilir mudik, begitu juga kapal yang mengangkut batu bara, dan di sepanjang tepian sungai yang pelatarannya sudah dibeton banyak anak-anak muda main sepatu roda. Jembatan yang melengkung itu konon meniru jembatan yang ada di San Francisco, dengan lampu-lampu kecilnya yang berkedip-kedip ketika senja dan malam tiba.
Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai Kertanegara, memang termasuk daerah yang pembangunannya pesat. Kantor bupatinya megah, begitu juga kantor DPRD yang hampir seluruh bagian mukanya dipenuhi dengan berbagai ragam hias. Sementara kantor-kantor dinas yang gedungnya kelihatan masih baru juga berkumpul di sekitar itu. Tak jauh dari jembatan nampak sebuah bukit yang dipenuhi bangunan-bangunan yang belum selesai, yang di antaranya hotel berbintang. Dan jika menyusuri ruas jalan ke arah utara kita akan bertemu dengan museum yang menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan lama. Reflika istana kerajaannya sendiri belum lama selesai direkonstruksi, letaknya tak jauh dari rumah dinas bupati. Meski semakin sayup suasana kota masih tersambung dengan rumah-rumah makan serta kios-kios souvenir sepanjang pinggir sungai.
Di tengah berbagai fasilitas pemerintah yang megah, saya membayangkan pasti terdapat juga gedung kesenian yang representatif, gelanggang olahraga yang lengkap atau sarana-sarana lain untuk aktivitas masyarakat. “Stadion sepakbola sudah lama dibangun, namun gedung kesenian belum ada,” ujar teman saya. Lalu teman saya tersebut menjelaskan bahwa hanya dalam radius sekitar dua kilo meter dari jembatan sudah bukan termasuk kota lagi, melainkan perkampungan biasa. Perkampungan dengan bentuk-bentuk rumah sederhana yang khas, rumah-rumah dengan atap seng. Tenggarong memang identik dengan jembatannya yang melengkung itu, di mana kantor bupati dan kantor DPRD sebagai pusat kekuasaan berada di hadapannya. Tiba-tiba saya merasakan sebuah ironi dari tata ruang kota ini, sebuah kontras yang tegas.
Dengan diantar teman saya memasuki perkampungan lebih dalam lagi. Di tengah-tengah perkampungan saya hampir tak menjumpai satu pun toko apalagi super market, yang ada hanya warung-warung kecil. Tapi yang kemudian membuat saya tertegun, saya menemukan banyak sekali papan nama dari berbagai komunitas kesenian. Ada yang menamakan komunitas tari, teater, musik, seni rupa dan semacamnya. Papan-papan nama yang dilengkapi logo serta nomer izin resmi tersebut terpasang di depan rumah, seperti halnya papan nama dokter atau pengacara yang membuka praktek.
“Di sini kesenian hidup di tengah masyarakat, banyak komunitas yang menghimpun anggota yang umumnya anak-anak dan remaja. Mereka secara rutin berlatih tari, teater, musik, senirupa dan sebagainya. Untuk teater atau senirupa biasanya dibimbing guru-guru SMK yang kebanyakan berasal dari Jawa, tapi kesenian yang ada kaitannya dengan tradisi dilatih seniman dari sini,” ujar teman saya yang berasal dari Yogyakarta. Kesenian-kesenian tradisional seperti tari dan musik, baik yang berbasis Melayu maupun Dayak sampai sekarang masih hidup.
Demikianlah, dalam atmosfirnya yang khas kegiatan kesenian terus berdenyut di Tenggarong. Setiap sore anak-anak dan remaja menari di halaman, di tempat lain sejumlah pemuda berlatih teater dan main musik. Ada juga yang teriak-teriak membaca puisi. Sementara ibu-ibu mudanya mengikuti senam aerobik dengan penuh semangat. Setiap komunitas mempunyai benderanya masing-masing, juga agendanya sendiri-sendiri. “Tapi kadang kita juga tampil bersama-sama. Tampilnya bisa di mana saja, bisa di lapangan, di gedung olahraga atau di kantor pemda. Untuk even tertentu malah sering diundang ke Taman Budaya Kaltim di Samarinda,” teman saya, yang juga melatih teater di salah satu komunitas, menjelaskan lebih jauh.
Kenapa komunitas-komunitas kesenian bisa terus hidup di Tenggarong? Di kota kecil yang minim sarana hiburan dan rekreasi ini, kesenian nampaknya mempunyai fungsi yang jelas. Bagi mereka yang menjadi anggota komunitas, kesenian merupakan media ekspresi serta sarana aktualisasi diri. Sementara bagi yang tidak terlibat secara langsung kesenian berfungsi sebagai pencerahan, paling tidak sebagai hiburan dan rekreasi. Dengan demikian, selain masyarakatnya yang memang membutuhkan, sedikit banyak pemerintah juga menyokong. Dalam hubungan timbal balik seperti inilah sebuah tradisi tercipta, yakni tradisi berkesenian. Dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat sendiri.
“Kesenian apapun yang digelar selalu banyak penontonnya,” lanjut teman saya yang mulai memperkenalkan latihan-latihan dasar teater mini kata kepada anak-anak didiknya yang masih remaja.
***
Lanjong merupakan salah satu komunitas yang ikut menyediakan wadah bagi anak-anak, remaja bahkan ibu-ibu muda untuk berkesenian. Tarian, dengan segala macam jenisnya mulai dari yang tradisional sampai dancer modern semua difasilitasi. Teater, mulai dari yang konvensional sampai kontemporer, begitu juga dengan musik dan sastra. Semua jenis kesenian diberi tempat dalam komunitas ini, termasuk juga yang berkaitan dengan adat. Tentu saja proses berlatih yang dilakukan terus-menerus dengan sendirinya akan menghasilkan banyak karya, yang pada gilirannya karya-karya tersebut harus dimasyarakatkan. Harus dipentaskan. Banyak cara yang kemudian dilakukan, mulai dari pentas-pentas sporadis di Tenggarong sendiri sampai melakukan road show ke kota-kota lain sekitar Kalimantan Timur. Bahkan beberapa kali sempat menyeberang ke Jawa dan Sulawesi. Dan yang menarik dari komunitas ini, hampir setiap pementasan selalu menggunakan naskah sendiri.
Setiap dua tahun mereka menggelar Lanjong Art Festival, sebuah festival kesenian yang kehadirannya mulai ditunggu-tunggu masyarakat. Pada awalnya festival ini sekedar peringatan ulang tahun berdirinya komunitas dengan hanya menampilkan para anggotanya sendiri. Namun pada tahun-tahun berikutnya festival menjadi lebih terbuka dengan mengundang komunitas lain di sekitar Tenggarong, bahkan pada festival yang terakhir sejumlah komunitas dari Balikpapan, Samarinda, Bontang serta beberapa seniman dari Jawa diundang menjadi peserta. Festival ini juga diramaikan dengan berbagai lomba dan workshop. Pementasan digelar malam hari sedang kegiatan-kegiatan penunjang dilakukan pada siang harinya. Setiap malam, gedung olahraga yang disulap menjadi teater tertutup ini selalu dipenuhi penonton, mulai dari anak-anak sampai nenek-nenek.
Dari tahun ke tahun Lanjong Art Festival mengalami semacam metamorfosis. Festival pertama mungkin terkesan seperti acara Agustusan, terutama karena harus mengakomodasi semua anggota komunitas untuk tampil. Tapi pada festival berikutnya konsep maupun materi acara menjadi lebih tertata, sedikit demi sedikit sistem kurasi diterapkan, juga pembagian kerja anggota semakin diperjelas. Jadi tidak semua anggota Lanjong ikut naik panggung, sebagian harus berperan di belakang layar. Dan masing-masing menjalankan tugasnya dengan penuh kegembiraan.
“Ke depan festival ini bukan hanya milik Lanjong saja, lambat laun masyarakat akan merasa memiliki juga,” kata teman saya yang sejak awal terlibat dalam pelaksaan festival. Harapan yang sama disampaikan oleh Nh. Dwinta Sari, ibu muda yang merupakan pendiri sekaligus pengelola komunitas kesenian yang cukup menonjol di Tenggarong ini. “Mudah-mudahan Lanjong Art Festival akan menjadi agenda resmi daerah sehingga pelaksanaannya bisa lebih terencana lagi,” ujarnya.
Pada festival tahun lalu saya dijadwalkan mengisi satu acara, namun teman-teman sepertinya mengharapkan saya untuk tinggal lebih lama. Maka saya pun bertahan hingga festival yang berlangsung selama seminggu itu usai. Saya menyaksikan semua acara dan kadang didaulat memimpin diskusi sehabis pementasan, terutama pementasan teater. Ada kebiasaan yang menarik di Kalimantan Timur ini, setiap pementasan teater selalu diakhiri dengan diskusi yang seru, yang tak jarang mengarah pada perdebatan sengit antar komunitas. Komunitas yang berasal dari Tenggarong, Samarinda, Balikpapan atau Bontang rupanya mempunyai konsep berteater yang berbeda satu sama lain. Hanya saja, jika diamati dengan seksama hampir semuanya mempunyai kecenderungan pada teater eksperimental. Rupanya trend teater tubuh, teater mini kata, teater perengkel jahe atau apapun istilahnya banyak peminatnya di kawasan ini.
***
Tahun 2010 ini, setelah pada tahun sebelumnya hanya menggelar pentas di sekitar Kalimantan Timur, Lanjong kembali merencanakan pentas keliling dengan menyambangi beberapa kota di Jawa. Pentas keliling yang diberi tajuk Lanjong Melancong ini akan dimulai pertengahan Juni ini dengan menggelar teater serta musikalisasi puisi pada sebuah festival seni di Surabaya. Lalu disambung dengan parade monolog di Tasikmalaya. Perjalanan akan dilanjutkan dengan sebuah repertoar di Bandung, di mana teater, monolog maupun musikalisasi puisi digelar serempak. Terakhir, pentas keliling ini rencananya akan ditutup di Jakarta.
Sebagai orang yang sempat merasakan suasana kekeluargaan di Lanjong, tentu saja saya menyambut dengan gembira rencana pentas kelilingnya ini. Lebih gembira lagi karena Lanjong akan mempertontonkan hasil pergulatan kreatifnya kepada teman-teman dan masyarakat Tasikmalaya. Dan sebaliknya teman-teman Tasikmalaya pun akan menunjukkan karyanya di hadapan mereka. Mudah-mudahan saja terjadi pergesekan pengalaman mengingat setiap daerah mempunyai kondisi serta atmosfir kesenian yang berbeda, yang memungkinkan untuk saling belajar satu sama lain. Pengertian komunitas di Tenggarong dan Tasikmalaya saja mungkin tidak sama. Di Tenggarong komunitas lebih dekat pada pengertian sanggar atau organisasi seni yang berbadan hukum dengan pengurus serta anggota yang jelas, sementara di Tasikmalaya komunitas dan sanggar lain, komunitas cenderung lebih cair.
***
Sekarang izinkan saya memberikan sedikit apresiasi kepada Nh. Dwinta Sari, yang selama bertahun-tahun telah mengasuh anak-anak muda Tenggarong dengan penuh kesabaran dan kasih sayang.
“Ya, karena saya merasa senang saja berkumpul dengan anak-anak dan yang lebih penting rumah kami menjadi selalu ramai,” begitulah jawabnya ketika saya tanya tentang latar belakang kenapa Lanjong didirikan. Sebuah jawaban sederhana untuk pekerjaan yang tentunya sangat tidak sederhana. Saya kemudian membayangkan betapa indah seandainya ibu-ibu di daerah lain juga melakukan hal yang sama. Hal yang kelihatannya kecil namun sangat bermakna.
Ibu yang satu ini bukan hanya menyediakan halaman dan sebagian rumahnya untuk latihan namun sekaligus menjadi motor penggerak bagi komunitasnya. Ia bersama beberapa seniman yang direkrutnya terjun langsung mengarahkan anak-anak muda tersebut ke jalan yang menurut saya merupakan jalan yang benar, yakni jalan kesenian. Jalan yang menjunjung nilai-nilai kreativitas. Jalan yang mengajarkan betapa pentingnya sebuah proses dalam kehidupan. Jalan yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan turut menyelamatkan bangsa dari kehancuran, baik yang berkaitan dengan mental, spiritual maupun sosial. Bukankah masa depan bangsa kita berada di tangan anak-anak muda? Begitulah. []